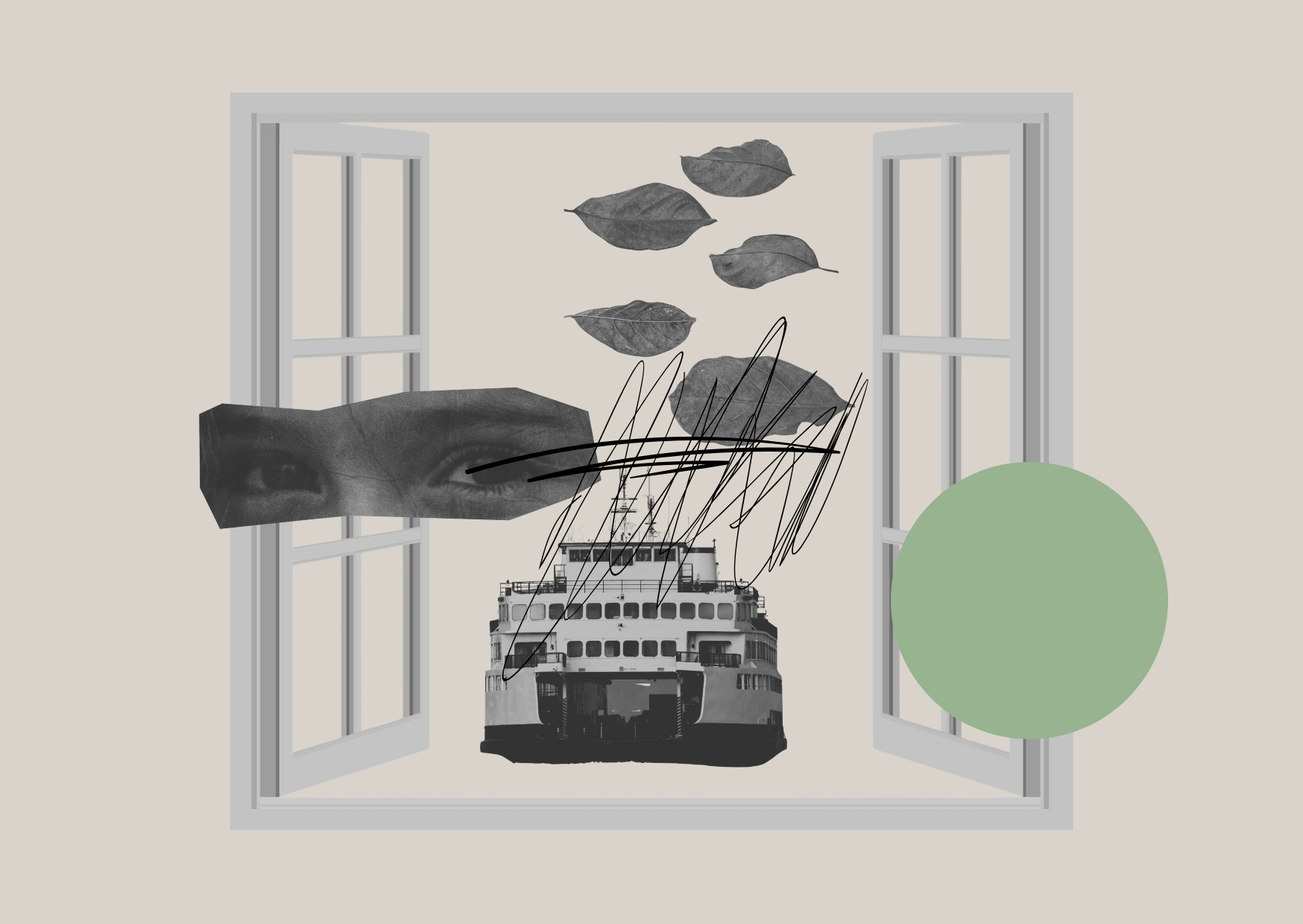
Mereka yang Merubuhkan Subuh
: 1960+
Mulai tahun enam puluh
setiap pagi masih jauh, abah
selalu memindahkan warna langit
ke pipinya dan ibu termenung
menimang kesedihan
dari balik pintu
baginya kemenangan, selalu
datang terlambat persis tambat
nasehat pengangkut barang
pada ferry terakhir
di tiap basah pelabuhan, dengan
dendam pada kejauhan
masa lalu
tetapi
ia tetap pulang hari ini
dengan kaos pedagang, tempat
senja menyimpan amis sungai,
aku menyambutnya riang:
“Abah memang hebat
wajahnya nampang
pada koran pagi, sedang
memeluk tiang pasar persis
gelang gigi hiu memeluk
lengan masa kecilku”
ia cuma diam seperti jam
seperti cermin retak tak
mengenang senyuman
seorang pun, tapi masih
diusapnya ubunku persis
renyai tempias menyemai
rasa lelah di bantal kami
tengoklah, tengok
abah terbaring menyamar
jadi obat nyamuk bakar
di kolong ranjang tempat
adik menyimpan tawa
di kaki lemari lapuk
yang tak mampu lagi
memikul beban
masa depan kami;
bertarung dengan decak cicak
usai lebih dulu bersitahan,
mengatup mimpi
yang tinggal separuh
rumah sebesar nasib, terselip
dalam keranjang daging,
tempat keturunan kami
memimpikan toko-toko
dan kios saling bersilangan
membelah jalan bikinan
negeri seberang,
”kalian
orang
terbelakang”,
katanya
apapun bahasa tak kami
mengerti, eja sebagai
kampung halaman
begitulah
surat izin usaha, pengap kota,
bertudung sunyi
di atas meja makan
(antara takut dan duka
dalam berkah sendawa)
tak ada lebih penting, selain
bingkai foto keluarga
ditukar selembar poster
bertuliskan,
“kami
menolak
relokasi”
sebagai penutup lubang
dinding-dinding dapur
dan tak ada jawaban.
Tak
ada
cuma tangis
adik sesekali,
menukar suara
perut lapar kami
juga lalat-lalat
berdengung
seakan berkata
“kalian
belum
kalah”
abah, mengapa ibu
tak ingin lagi
menimang kami?
2025
Setelah Katedral Samarinda
Engkau tak tahu, satu-satunya
tersisa di mataku adalah
jendela tak terkunci,
tempat anak-anak melarikan
diri dari sekolah yang lebih
membelenggu dari perangkap
guru usai kabur ke bulan-
bulan di kalender yang
tak ada tanggal merah
Nyanyian-nyanyian harapan
dijepit pekik sirine pemadam
dan dadaku dipenuhi bangkai-
bangkai mainan; Egrang, Gasing,
dan layang-layang, kutarik harga diri
yang lebih murah dari buku-
buku pelajaran juga mercon Busi;
hidup cuma meletupkan trauma
masa lalu dan bau mesiu itu,
menguar melalui napas
lelah mulut ibuku
Sepotong bayang wajah kecilku
tak lagi selenggang dulu,
ia terkaca pada banjir kampungmu
menanti dilarutkan waktu
ke parit seperti puisi, menggenang
ke bendungan folder. ke trotoar,
dilindas truk, mengering,
lalu disapu tukang
pembersih jalan
sedang ayahku,
dapatkah kau bayangkan,
usai terbenam ia di beranda
menghela sakitnya
sabung ayam dan judi online?
Aih bungul,
impian serupa Tempakul
terbenam di sandal dan bungkus sampo
memikul-mikul kesedihan
di balik lumpur usia
dapatkah aku sematkan
telur nasib ke di dinding
-dinding doamu?
Bagaimana engkau tahu,
minggu pagi ini aku ketiduran
tak ada jendela untuk melarikan diri
sedang anak kecil dalam diriku
tak henti-hentinya mengejar
layang-layang
mengapa tak di matamu?
2024
Sepinggan
Dan di piring waktulah
turis-turis itu mendarat
dengan garpu dan pisau di tangan
yang matanya tak mau mengerling
dari batang leher saudaramu
(kau tahu bahwa setiap hidangan
hanya wajah kegembiraan
yang sepenuhnya meragukan)
“Apalah lagi hendak kau santap meneer,
sebab, matahari hanya kuning ceplok telur
yang kita sisakan pada suapan terakhir;
terik yang sunyi sebuah pulau
dengan musim yang tak pasti”
Namanya dijajah sayang,
kehidupan tak mungkin sehalus
menyelai punggung roti, tatkala
hari-hari mengibar pergi pada 1527
kali itu bandara kuyup, bau aspal basah
yang membuatmu bertanya,
“Beginikah pula bau muntahan
orang lapar di kelasi, yang mengendurkan
jalur sungai dari pergelangan nadi kami?”
Usia hanya retak tanah
pada makam moyangmu
yang kadang tak berbentuk
seperti masa lalu, juga
patahan-patahan tombak
dikerat akar dan lumut
yang tertimbun menjadi rahasia
(kau menduga itu milik budak dari
negeri seberang yang pernah
menjemput kepulangan ibumu)
“Kami tahu baginda Jayakarsa akan angkat bicara,
dan memenggal kepalanya”
Tapi kau tak mau aku ikut menjelajahi
kisah perih dalam lintasan pulau ini,
sebab kau tahu, akan ada kapal-kapal
melabuhkan sejarah dan pesawat
yang mendarat sekaligus memuntahkan
dongeng tentang leluhurmu sedang
di tengah ladang itu, rumah hilang makna
tinggal tiang Lamin tempat saudaramu
menyematkan Bening dan Jala
yang menyimpan amis iwak persis
angin membangunkan api
pada umbul rambut rimba;
segumpal kabut kenangan pada bukit
yang menghalau mata
pada sebuah jurang
yang ingin kau jengkal sampai
ke lubuk ingatanmu,
Dan kau tahu di piring waktulah
bahwa setiap hidangan
hanya wajah kegembiraan
yang tak membuatmu berarti
2023/2025
Bening
Bukanlah iwak
dikau yang aku timang
di balik punggung nak,
dan sebagai penunggu sungai
yang meruas arus di pusarmu
tak berarti karena berkulit licin
kita saling berlepasan
terperangkap jala-jala kota yang dingin
dari Hulu ke Ing Martadipura
adalah kecemasan, katamu
Kau kenali aku,
lewat petunjuk langit sembab
adalah mata penjinak gaung gelombang
yang terhenyak kaku serupa Baung
lepas dari tombak, begitulah jika kau lihat
betis kampung yang pincang
macam nyiur tumbang
usai disepak tongkang
Kabarnya,
seorang bangsawan yang tengah lelah
menyusun embun dari langit Timur
adalah rengekmu nak, riuh Harimau
yang mengasah kukunya ke badan
risalah kampung halamanku
(alamak janganlah buat pula tanda
agar pemburu pulang kemari)
“Pasang taringku untuk Beningmu,
sebelum tumpul dan copot oleh orang kota
buat cangklong dan hiasan dinding
O, kabarkan aum ini ke ladang
ayun aku dalam budi luhurmu, Ine”
Di kampungmu ini,
peristiwa terkubur dan
musim-musim tak tanggal di dada
sementara kelahiran terus terjadi,
Mahakam terbuat dari liang dan tongkang
dan bau lembah batu
kian dengus ke ubun pagi
seperti kematian janggal
moyangmu, rekah
dari sepah-sepah
di lidah kompeni
Nak, jikalau kau tahu kehidupan kita
terkamlah segala pendatang
jangan sembunyi bagai tapai,
di hidung manis
kelat ia ke muka
tapi harus wani bagai umbi,
dari tanah ia memberi,
memberi ke rumah sunyi,
ke punuk malam, ke bilik-bilik pagi
seakan-akan kau bertamu
pada rasa lapar yang tak pantas
untuk seorang penakut
Maka jauhilah remang, sebab
apa yang hendak dirampas
dalam rahim sempadan lainnya
yang berdarah adalah
aroma daun basah
dari tanda rinai terakhir
titisan datuk leluhurmu
yang dijawab pokok-kayu
sebagai rimba masa lalu
2022/2024
- Puisi Novan Leany - 18 November 2025

AAM
Bagus ini puisinya maknanya dalam semua. Isu dan pesannya tersampaikan. Saya paham bgt krn pernah rantau juga ke Samarinda, Kaltim