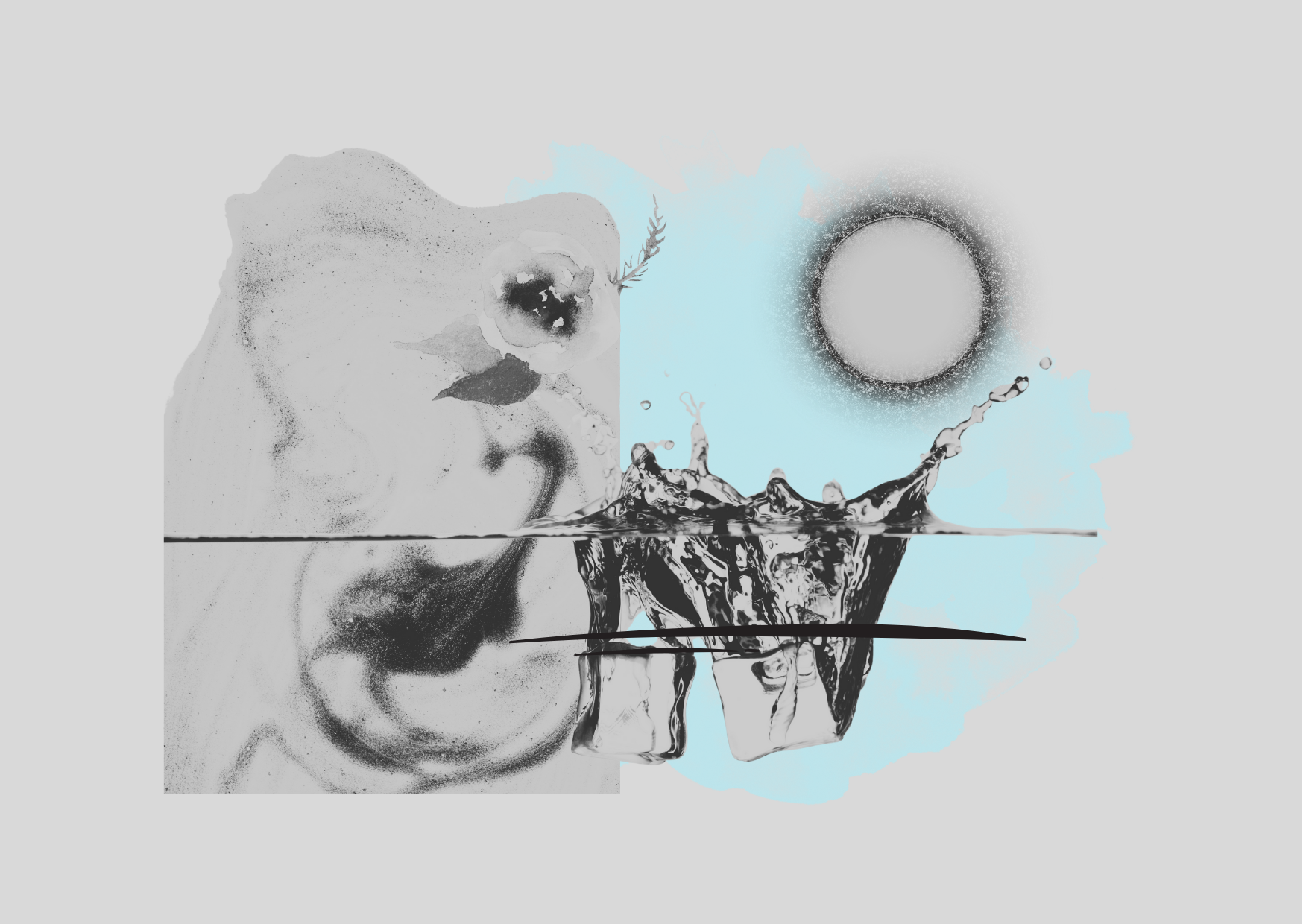
Surat-Surat Penyair yang Tak Pernah Dibacakan
- Surat dari Meja Kayu Patah
Aku menulis dari meja tua yang dilukai rayap dan waktu
Dengan tinta yang kuaduk dari sisa kopi dan airmata.
Bangsaku,
Apa kau masih mengingat penyairmu?
Yang dulu kau minta mengubah lapar jadi lagu
Dan luka jadi mars berbaris rapi?
Kau beri aku panggung—
Tapi tak pernah kursi
Kau minta aku menulis—
Tapi tak pernah membaca
Kau simpan puisiku di lemari dinas
Dan menyiarkannya di pagi peringatan
Namun tak sekali pun kau tanyakan
Bagaimana kabarku malam itu
Saat huruf-hurufku gagal membayar kontrakan
- Surat dari Kolong Panggung
Merdeka, kau ucapkan
Dengan suara serak seremonial
Sementara di bawah panggung
Aku duduk di kolong
Menghapus nama-nama
Yang dilarang disebut dalam sajak
Kau takut pada kata yang jujur
Lebih dari peluru
Kau ganti kata “perut kosong”
Dengan “gizi cukup”
Kau cabut baris tentang kampung
Yang ditenggelamkan proyek nasional
Dan menyelipkan slogan
Yang tak kutulis
Tapi aku diam
Karena diam kadang satu-satunya kemerdekaan
Yang belum kau cukai
- Surat kepada Anak yang Tak Punya Tempat Bertanya
Anakku, jika suatu hari kau temukan buku puisiku
Berdebu di rak perpustakaan desa yang sepi,
Bacalah dengan pelan
Karena itu bukan sajak biasa
Itu adalah surat yang kusembunyikan
Dari sorotan kamera
Dan dari lengan panjang cengkeraman negara
Di sana aku titipkan
Sejarah yang dipotong
Dan fakta yang dimaniskan
Kau akan tahu,
Bahwa kata “kemenangan” di puisiku
Selalu terluka
Selalu bocor
Karena tak pernah benar-benar jadi milik kita
- Surat Terakhir dari Lidah Berdarah
Bangsaku, aku tidak menyesal menjadi penyair
Meski kau tak pernah menjemput puisiku pulang
Aku tak ingin dimakamkan di taman pahlawan
Cukup di kaki pohon randu
Di kampung yang tak ada di peta
Di mana kata-kata masih bernyanyi tanpa izin
Karena selama masih ada satu kalimat
Yang ditulis tanpa takut,
Satu sajak yang dibisikkan diam-diam di warung kopi,
Satu anak kecil
Yang bertanya mengapa rakyat harus ikut lomba panjat pinang
Untuk hadiah mie instan—
Selama itu pula
Aku akan tetap menulis
Meski kau tak pernah membaca
(2025)
Ars Memoriam Minus Homo
Tak ada nama yang disematkan di batu prasasti.
Hanya lekuk jemari yang mengerti:
siapa yang menatah dada patung itu
dengan nadi getir dan logam lengang.
Hari ini, bendera kembali dikibarkan
seperti selembar luka yang disetrika:
rapi, merah-putih, tapi masih bau
daging terbakar dalam ukiran sejarah.
Aku tak ikut upacara.
Terlalu banyak mata menghadap langit,
lupa bahwa kemenangan kerap ditanam
oleh yang tak sempat menyebutnya doa.
Tropi itu kini dipoles ulang saban Agustus,
disapu pel dan nasionalisme tipis-tipis.
Namun tak seorang pun menyeka debu
di punggung para pematung yang dilupakan.
(2025)
Teh Poci dalam Kepala Ayam
di warung sepi dekat kuburan,
kami menakar persahabatan
dari seberapa panas teh poci menahan hujan sore.
tak ada kata “kawan”
hanya dua kursi plastik
dan ayam mati yang jadi penunjuk arah
di kepala kita.
kau menyebut namaku seperti membaca mantra rusak,
dan aku membalas dengan
isyarat dari asap rokok kretek
yang tak pernah kau isap tuntas.
kita tak pernah sepakat
apakah dunia ini nyata
atau hanya amplop kosong
yang dikirim nenek moyang
dari desa yang sudah tenggelam dalam mimpi sendiri.
persahabatan, barangkali,
adalah ketika kita duduk
tanpa bicara sepatah pun,
namun sama-sama tahu
bahwa bulan di atas kepala itu
sebetulnya hanya tutup dandang
yang jatuh dari langit
tiga lebaran lalu.
(2025)
Sabuk Van Allen di Dada Chairil
Di antara khatulistiwa syaraf dan parabola kenangan,
kami mengikat tubuh pada sabuk Van Allen—
bukan untuk perlindungan, tapi
untuk mengukur berapa banyak puisi
yang bisa bertahan
di luar gravitasi makna.
Ada kata-kata yang hampa udara,
ada bait yang kehilangan tekanan
di atmosfer ketiga
tempat pertemanan kami menggigil
di antara serbuk bintang
dan derau sunyi tape rekaman puisi 1954.
Kami, dua zarah yang saling mengorbit
tanpa peta, tanpa deklinasi,
cuma dendam yang diputar ulang
di mesin kaset rusak perpustakaan planetarium.
Kau, penyair dengan dada kawah lunar,
menyematkan sajak ke gesperku:
“jangan percaya bumi
jika mulutnya belum pernah menganga untukmu.”
Kita duduk di antara sela-sela langit
memainkan satelit buatan
yang diretas dengan metafora—
setiap parabola menjadi salib,
setiap jeda menjadi jendela
untuk melompat dari satu musim ke gugus
tanpa harus punya nama.
Persahabatan kami bukan urat tangan,
melainkan ruang lengang
antara peluncuran dan kehilangan,
antara pelukan dan perpisahan
yang ditulis pakai gelombang radio
frekuensi rendah
dan dikubur di dada waktu.
Ada yang bilang
puisi tak perlu sabuk pengaman.
Tapi aku masih menyimpan
gesper logam itu,
dengan ukiran orbit tak selesai,
dan sebutir debu supernova
yang kautinggalkan
di sela huruf-hurufku
yang tak lagi bisa kembali ke bumi.
(2025)
- Puisi Moehammad Abdoe - 6 January 2026

Abil. Q
RENYAH
Yuhesti Mora
“Dilukai rayap dan waktu” itu sungguh larik yang kuat dan meninggalkan kesan.
Simbol dari luka-luka kecil, rutinitas dan kekecewaan sehari-hari yang terakumulasi dalam jangka panjang.
Dan kenapa tulisannya dilabeli “surat” dan bukan disebut “puisi”. Penulis seolah ingin menegaskan bahwa yang ditulis ini pada akhirnya adalah sebuah arsip batin yang harus dicurahkan, sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada seseorang bukan tentang pertunjukan karya.
Purwati
Luka masalalu yg harus segera diselesaikan tolonggggg
nawaa
puisinya keren bangettt! aku suka
cins
keren bgtt!!!!
Ann.
Keren, mas. 🙌
Ida
Suka sekali