Sebuah sudut di pertokoan yang hanya berjarak dua blok dari kantorku selalu menarik perhatianku setiap kali aku melewatinya. Bukan sudut yang memamerkan pakaian mewah atau tas mahal seperti yang seharusnya aku cari-cari setiap hari sebagai bahan baru untuk artikelku. Sebuah sudut itu adalah counter handphone bernama Berlian Cellular milik seorang kenalanku yang aku kenal dari Nadya, seorang temanku yang merupakan langganannya. Aku tak begitu mengindahkannya ketika pertama kali bertemu, tapi suatu kali aku bertemu secara tak sengaja dengannya di sebuah warung bakso, masih di dekat lingkungan kantorku. Saat itu, aku baru tahu namanya Azhar, itu setelah dia meminta izin untuk duduk di sebelahku dan menyebutkan namanya, “Azhar, Berlian Cellular. Ingat, kan?” ujarnya, seolah ia tahu aku benar-benar melupakannya.
Lalu kami bicara tentang banyak hal, ia sering makan bakso di sana karena hanya bisa makan daging sapi dan sayur, tidak bisa makan ayam dan semua macam ikan dan seafood tanpa menjelaskan apa sebabnya. Dia juga bilang suka kopi; itulah awalnya aku dan Azhar memulai persahabatan kami.
Waktu makan siangku sering kuhabiskan bersamanya, makan bakso, minum kopi di sebuah sudut coffee shop yang dikelilingi jendela kaca. Dia juga sering menemaniku mencari pakaian dan sepatu model terbaru yang akan kutulis untuk artikel di majalah mode tempat aku bekerja sebagai seorang editor. Kadang ketika dikejar deadline, aku memintanya untuk memotret benda-benda yang akan kupilih untuk kumasukkan ke dalam artikel dengan sebuah kamera digital kecil ukuran saku yang terus kubawa ke mana-mana. Aku menikmati menemani saat ia bekerja di counter miliknya, melayani pembeli dengan bahasa khas seorang marketing andal yang pandai merayu. Aku sering menggodanya dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang perayu andal, aku berharap bisa melihatnya merayu seorang wanita. Tapi, suatu kali aku dikejutkan oleh pernyataannya.
Siang itu, kami duduk di coffee shop, menikmati secangkir kopi hitam. Dia mengatakan bahwa aku tak akan pernah bisa melihatnya menjadi perayu andal yang akan merayu wanita karena ia akan segera menikah. “Aku tidak perlu merayunya. Ini sebuah pernikahan yang diatur oleh keluarga kedua belah pihak.”
Hal yang tak masuk akal itu kudengar dari mulutnya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, tapi pernyataan Azhar barusan membuatku seperti terlempar jauh ke masa itu. Perjodohan seperti suatu budaya dalam keluarganya. Azhar adalah pria keturunan campuran India dan Pakistan. Ketika partition time, saat Pakistan memisahkan diri dari India pada tahun 1947, kakek Azhar yang orang Pakistan dan saat itu baru berusia lima belas tahun memutuskan untuk melarikan seorang gadis Hindustan seumurannya ke sebuah negara bernama Indonesia, di mana perbedaan mereka menjadi bukan suatu masalah hanya karena mereka telah dijodohkan sejak kecil jauh sebelum partition. Aku tak bisa membayangkan betapa besar keberanian dan keyakinan keduanya untuk meninggalkan tanah air mereka demi mempersatukan cinta. Setelah bertahun-tahun menetap dan menjadi WNI, keluarga mereka tetap mempertahankan tradisi dalam banyak hal. Azhar bercerita banyak padaku tentang keluarganya, bagaimana orang tuanya dipertemukan dalam perjodohan untuk mempertahankan tradisi mereka. Dan, sekarang ayahnya ingin ia menikahi seorang gadis yang orang tuanya berasal dari Gujarat. Ia sudah beberapa kali bertemu gadis itu, dan Azhar menyebutnya “manis dan cantik”.
“Aku turut bahagia untukmu.” Aku berusaha mengucapkannya dengan tulus, tapi tetap terdengar datar di telingaku sendiri.
Hari itu, saat keluar dari coffee shop, kami berjalan sendiri-sendiri, berlawanan arah. Aku harus pulang ke kantorku dan Azhar kembali ke counter-nya. Hujan turun perlahan, aku menarik keluar sebuah payung mungil dari tas Gucci kesayangan yang baru kubeli beberapa bulan lalu. Azhar yang memilihkan tas itu untukku saat ia menemaniku berbelanja beberapa keperluan untuk pemotretan sampul majalah.
“Sedia payung sebelum hujan, meski dalam tas Gucci-mu yang mahal, agar tasmu tidak kebasahan.” Nadya sering mengatakan itu padaku. Aku tahu seharusnya aku siap seperti sekarang, siap untuk mendengar apa yang baru saja kudengar tentang rencana pernikahan Azhar. Tapi, Azhar bukan sebuah tas Gucci mahal, dia lebih dari itu dan aku tak punya persediaan payung yang tepat untuk persahabatan kami yang mahal.
***
Aku memutuskan menerima tawaran pemimpin redaksi untuk menjadi koresponden freelance meliput perkembangan mode di Eropa. Sebelumnya aku tak punya keberanian untuk menerima tawaran ini, tapi setelah Azhar memberi tahu tentang rencana pernikahannya itu, aku tak punya pilihan lain. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa kami hanya bersahabat, tak perlu ada perasaan melankolis meskipun aku akan selalu mengingatnya setiap kali menikmati secangkir kopi hitam, mengingat bagaimana cara Azhar memegang cangkir dengan tangannya yang besar tanpa memegang gagang cangkir, seolah panas dari cangkir itu adalah sesuatu yang juga tak ingin ia lewatkan selain sesapan ketika menghirup kopi panas. Pun, ketika memandang ponselku itu juga akan selalu mengingatkan pada Azhar karena banyak fotonya tersimpan di ponselku. Bukan karena Azhar tinggi dan tampan layaknya bintang film Bollywood, tapi ada sesuatu yang hangat mengalir di tubuhku setiap kali bersamanya.
Aku menggenggam erat sebuah undangan yang dikirim Azhar ke apartemenku. Besok adalah hari pernikahan Azhar, dan aku sengaja memilih hari ini untuk pergi meninggalkan Indonesia. Tapi, tadi malam aku melakukan sesuatu di luar kesadaranku. Aku mencoret nama calon pengantin wanita dan menuliskan namaku di atasnya sehingga tertulis: Akan dilaksanakan pernikahan antara Azhar Das dan Mula Wardhani.
Aku menggelengkan kepala seperti orang gila. Sebelum meninggalkan apartemen, aku meletakkan undangan itu di atas tempat sampah di sebelah pintu apartemenku. Aku meninggalkannya di sana, juga semua tentang Azhar, demi karierku.
***
Tak terasa lima tahun telah berlalu, banyak hal yang telah kulalui di Paris, Milan, London, dan Madrid. Aku merasa sudah cukup tangguh untuk kembali ke Indonesia ketika pemimpin redaksi di majalah tempatku bekerja memutuskan untuk pensiun. Ia akan digantikan oleh Nadya, salah seorang seniorku di dunia editor fashion dan juga teman lamaku. Nadya yang memintaku pulang untuk menghadiri acara pengukuhannya sebagai pemimpin redaksi. Ia memintaku kembali jadi editor senior yang akan membantunya mengembangkan majalah fashion kebanggaan kami.
Kantor kami tak banyak berubah, hanya susunan meja dan partisinya saja yang berubah desain, lebih chic dan modern dengan gaya minimalis. Orang pertama yang kutemui di sana adalah Nadya yang menyambutku dengan penuh keakraban.
“Aku senang akhirnya kau pulang. Aku merasa kau harus ada di sini, mendukung saat aku mencapai puncak karier.”
“Karena aku pernah ada di bawahmu, menjadi pijakanmu agar kau menjadi editor senior waktu aku baru mulai bergabung di sini, iya, kan?” Aku menggodanya dengan gurauan.
“Memang tak akan pernah bisa tanpamu, Mula.” Nadya tertawa lepas mendengar gurauanku.
“Bagaimana pesta pengukuhannya minggu depan?”
“Sudah siap delapan puluh persen. Kau tidak usah mengkhawatirkan itu. Aku ingin memintamu melakukan sesuatu…. Untuk edisi perdanaku sebagai pemimpin redaksi, aku ingin kau membuat sebuah artikel eksklusif tentang perempuan sukses yang masih lajang di atas usia tiga lima.”
Aku melongo beberapa saat. Kenapa harus aku? Kenapa tema seperti itu?
“Karena begitulah aku sekarang.” Nadya berujar seolah tahu apa yang kupikirkan. “Aku ingin mencari lebih banyak role model untuk menjadi teman sekaligus panutanku.”
“Sesederhana itukah? Aku kira kita akan membahas tentang fashion.”
“Dunia sudah banyak sekali berubah, wanita lajang di usia matang biasanya lebih memperhatikan tubuh dan penampilan mereka daripada perempuan usia ABG. Kau tahu sebutan untuk perempuan ABG gaul sekarang di sini? Cabe-cabean!” Nadya memberi penekanan pada kata-kata terakhirnya.
“Norak,” sahutku.
“Itu kau tahu.”
Aku menarik napas dalam, berusaha memahami tema yang diberikan Nadya dan mengira-ngira siapa saja yang mungkin akan aku temui untuk artikel ini.
“Aku sudah membuat daftarnya, pergilah bersama fotografer freelance kita. Kau akan menemukannya di studio kita, dia sedang memotret beberapa model untuk iklan majalah.”
Aku menuju studio dengan gontai. Banyak orang baru di sini, hanya beberapa yang kukenali. Aku menemukan seorang fotografer sedang memotret beberapa model. Dilihat dari belakang, tubuhnya tinggi semampai dan berkulit gelap, rambutnya bergaya undercut, dan ia memakai anting di kedua telinga. Aku berusaha mengingat-ingat kenapa pria itu mengingatkanku pada Azhar, tapi tak mungkin dia menjadi seorang fotografer freelance. Aku tahu itu bukan bidangnya. Namun, ketika ia memerintahkan seorang model untuk mengubah posenya, aku tahu itu Azhar, dari suaranya yang berat dan dialeknya yang khas. Aku menunggu ia selesai dengan hati berdebar.
“Azhar…,” panggilku.
Azhar menoleh dan wajahnya tak dapat menyembunyikan keterkejutan melihatku berdiri mematung di hadapannya.
“Kau benar-benar pulang?” tanyanya seolah tak percaya.
“Seharusnya aku yang bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kau? Fotografer freelance?” Aku menggelengkan kepala, tanda tak percaya.
Azhar tersenyum mengembang, dia terlihat begitu manis.
“Kau traktir aku secangkir kopi, baru kemudian kita bercerita. Aku juga ingin tahu apa yang kau lakukan selama di Eropa. Menghindariku?” Azhar menatapku tajam.
“Apa?” Aku terkesiap beberapa saat dan gugup.
Azhar tersenyum, seolah yang baru saja kudengar hanyalah semacam gurauan. Aku bernapas lega. Kemudian ia menghentikan semua pekerjaannya dan memakai jaketnya terburu-buru. Lalu, ia menggamit lenganku. Aku merasa tak nyaman diperhatikan begitu banyak orang. Apa Azhar lupa dia sudah jadi suami orang? Orang-orang pasti berpikir yang tidak-tidak tentang kami.
Aku diam saja ketika Azhar menyuruhku naik ke sebuah motor Kawasaki Ninja miliknya, aku merasa Azhar sangat berbeda dari Azhar yang dulu kukenal. Kuakui, dia lebih menawan sebagai seorang pria yang semakin matang namun tetap berpenampilan muda. Seingatku dulu dia tidak memakai anting, apakah setelah menikah dia bertransformasi menjadi seperti yang sekarang aku lihat?
Kami duduk di tempat biasa seperti lima tahun lalu, di sudut coffee shop. Dia memandangiku begitu lama. Tak bicara apa pun. Membuatku gugup.
“Apa yang sedang kau lakukan? Aku tidak nyaman kau memandangiku seperti itu.”
Aku memalingkan wajah ke arah jendela untuk memandang ke luar dengan leluasa. Aku mendengar Azhar menarik napasnya dengan sangat dalam.
“Lima tahun kau tidak menghubungi aku. Kau mengerikan, aku kira kau tak akan pernah meninggalkanku seperti itu, tapi kau melakukannya. Aku terluka….”
“Kau bicara apa? Aku pergi untuk bekerja di negeri orang, kadang aku berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat. Aku tak punya banyak waktu, bahkan untuk diriku sendiri,” aku beralasan.
Azhar masih memandangiku dengan tatapan yang aneh. Aku sangat merasa tidak nyaman.
“Aku tidak membawanya…. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, tapi aku tidak tahu kau akan datang hari ini, jadi aku tidak membawanya.”
“Apa?”
“It’s just something.” Azhar tersenyum dengan tatapan menggoda. Aku benci itu. Apakah Azhar melakukan hal seperti itu pada model-model cantik yang ia foto? Apakah pernikahannya tidak bahagia? Apakah sesuatu terjadi pada pernikahannya?
“Bagaimana bisa kau menjadi fotografer freelance di kantorku? Bagaimana dengan counter milikmu?
Azhar masih tersenyum sebelum menjawab. “Karena kamu. Kau mengajakku berkeliling untuk memotret begitu banyak barang fashion, apa kau tidak ingat? Setelah kau pergi, aku mengikuti kursus fotografi dan kemudian Nadya tertarik pada hasil jepretanku. Nadya yang mengajakku bekerja sebagai freelancer. Aku menyukainya. Dan, counter HP itu sudah sangat berkembang. Aku punya seorang manajer untuk setiap cabang, jadi aku tidak perlu setiap hari ke sana, hanya di akhir pekan saja.”
“Manajer? Cabang? Wow…, kau punya sebuah perusahaan, bukan sebuah counter.” Aku terkejut.
“Iya, aku sudah menjadikannya sebuah perusahaan.”
“Cukup tentang itu, berapa orang anakmu sekarang?” Aku bertanya penuh penasaran.
“Masih belum ada.” Wajah Azhar sedikit berubah sendu. Dia pasti sangat sedih karena setelah lima tahun menikah belum juga memiliki anak.
“Maaf aku sudah menanyakan hal itu,” kataku penuh penyesalan. “Bersabar saja, mungkin masih belum rezeki.”
Azhar menatapku dengan tatapan kosong. Aku menyesal sekali telah menanyakan hal itu.
***
Azhar menemaniku menemui beberapa narasumber untuk diwawancarai, mulai dari reporter televisi, CEO sebuah perusahaan pengembang software, desainer ternama, hingga perwira polisi yang sangat elegan. Semuanya masih melajang dan punya penampilan high class seperti model ternama. Aku menikmati wawancara dengan mereka satu per satu. Tapi, perwira polisi yang sudah berpangkat AKBP itu menyadarkan aku tentang sesuatu.
“Saya terkadang menyesali pilihan hidup untuk melajang, tapi ketika menyadarinya, saya sudah hampir berkepala empat. Dulu pernah ada seorang pria menginginkan saya, dia seorang bintara tapi tentu saja saya berpikir dia tidak akan sebanding dengan saya. Saya takut dia akan merasa minder jika suatu hari kami menikah dan saya lebih dominan daripada dia. Tapi, pada akhirnya itu hanya ketakutan saya saja. Setelah berakhir dengan saya, dia menikahi seorang dokter dan saya tahu dia bahagia. Kadang kita seperti itu, terlalu takut pada apa yang belum benar-benar terjadi. Mungkin itu adalah kebiasaan saya dalam bertugas, untuk mengantisipasi banyak hal buruk dalam masyarakat. Tapi terkadang manusia bisa salah, kan?”
“Apakah itu yang menjadi alasan Anda masih melajang sampai sekarang?” tanyaku hati-hati. “Maaf, ini hanya keingintahuan saya saja, off the record,” aku menjelaskan.
Dia berpikir sejenak, kemudian menjawab, “Saya masih membandingkan semua pria yang mendekati saya dengan pria itu. Saya masih belum menemukan tipikal yang hampir sama atau setidaknya mendekati.”
Selama wawancara berlangsung, Azhar merekamnya untuk dimasukkan ke website. Dia kelihatan tegang dan serius ketika aku menanyakan hal pribadi itu kepada sang perwira polisi.
Kemudian, pada sesi berikutnya, sang perwira polisi menunjukkan isi lemarinya. “Ini pelarian saya, seperti memiliki anak-anak sendiri ketika merawat koleksi tas dan sepatu saya,” ungkapnya. “Saya lebih sering memakai seragam ke kantor, jadi tas yang indah akan membantu untuk lebih menonjolkan sisi feminin saya.” Aku mengangguk tanda setuju.
***
“Kau lihat perwira polisi tadi?” tanya Azhar ketika kami menghabiskan sore itu di warung bakso favorit kami.
“Tentu saja aku melihat semuanya. Dia punya selera yang tinggi pada tas dan sepatu meskipun di kantor dia harus pakai seragam. Cara berpakaiannya sehari-hari juga agak maskulin.”
“Bukan itu. Penyesalannya. Apa kau melihat bibirnya bergetar ketika ia mengatakan menyesal?”
Aku berusaha mengingat. Aku tak memperhatikannya terlalu detail, jadi aku menggeleng, kemudian melanjutkan melahap bakso.
“Aku menyesal,” ucapnya pelan. Hampir saja aku tak mendengarnya.
“Kau menyesali apa? Pernikahanmu? Kau tidak puas dengan istrimu atau kau kecewa karena dia belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan? Apa karena itu kau bersikap genit di hadapan banyak wanita?” Aku menumpahkan kecurigaanku pada sikapnya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dia menunjukkan sifat agresif terhadap wanita di hadapanku seolah dia belum menikah.
“Kau benar-benar tak tahu apa pun?” Gantian Azhar yang menatapku penuh selidik.
“Apa?” Aku semakin bingung dengan sikapnya.
“Sudahlah.” Azhar mengakhiri perbincangan kami sore itu.
***
Aku menyerahkan artikel pada Nadya setelah semuanya selesai dan Nadya cukup puas dengan hasil kerjaku, maksudku hasil kerja aku dan Azhar. Sebelum keluar dari ruangan Nadya, aku teringat sesuatu.
“Nad, apa kau tahu apa yang terjadi pada Azhar belakangan ini? Aku melihat dia agak aneh, jauh berbeda dengan Azhar yang aku kenal dulu.”
“Aneh bagaimana?” Nadya balik bertanya padaku.
“Aku merasa dia sedikit jadi lebih penggoda. Kemarin dia mengatakan menyesali sesuatu. Aku pikir itu terkait dengan pernikahannya. Apa dia dan istrinya baik-baik saja?”
Nadya memandangku lama, mencari-cari sesuatu di wajahku. “Kau benar-benar tidak tahu?”
“Apa?”
“Oh…, aku tahu. Saat itu, kau berangkat ke Eropa. Kau berangkat satu hari sebelum pernikahannya, bukan?”
Aku berpura-pura mengingat-ingat. “Kurasa begitu,” jawabku.
“Dia belum menikah.” Nadya mengejutkanku. Aku yakin mataku membelalak hampir keluar.
“Ke-kenapa? Ada apa?” Aku tak bisa menyembunyikan kegugupan.
“Sesuatu terjadi. Gadis itu lari bersama pria lain satu hari sebelum hari pernikahan mereka. Aku pikir kau tahu hal itu…, karena seingatku dia pergi ke apartemen lamamu setelah menghambur dan menangis padaku.”
Nadya memang seperti seorang kakak bagi Azhar, aku tak heran jika Nadya orang pertama yang akan ia temui pada saat itu.
Aku termangu. Mungkin, kami selisih jalan pada saat itu.
“Sudahlah, itu sudah lama terjadi. Tak usah kau ingatkan dia lagi tentang itu. Bagaimana kalau kau ajak dia untuk pesta nanti malam? Kau akan datang, kan? Datanglah bersamanya.”
Aku hanya mengangguk sesaat sebelum meninggalkan ruangan Nadya dengan langkah gontai.
***
Aku menemukannya di coffee shop bersama secangkir kopi dan sebuah muffin. Aku masih pura-pura tak tahu apa pun meski aku tak bisa menahan debar di hati. Azhar diam saja, membuatku tak tahan untuk tidak mengusiknya. Aku ingin meminta maaf padanya tentang ketidaktahuanku.
“Maafkan aku, aku tidak tahu mengenai pernikahanmu yang batal.” Aku menundukkan kepala, ingin menunjukkan penyesalan yang dalam.
Azhar menaruh sesuatu di atas meja. Sebuah undangan pernikahan seperti yang pernah aku terima darinya dulu. Aku menatap undangan itu, sudah terlihat usang, tapi masih dalam lipatan yang bagus. Aku beralih menatap Azhar.
“Bukalah!” perintahnya tegas.
Aku mengambil undangan itu dan membukanya, aku menatap Azhar terkejut ketika menyadari bahwa undangan itu adalah undangan yang dikirim ke apartemenku dan kucampakkan di tempat sampah sebelum aku berangkat ke Eropa. Masih tertulis: Akan dilaksanakan pernikahan antara Azhar Das dan Mula Wardhani. Nama Canthini telah kucoret-coret dengan pena hingga tak terbaca lagi.
Napasku seakan berhenti sesaat. Aku tak berani menatap Azhar lagi dengan rasa malu yang sangat.
“Aku menyesal tidak punya keberanian seperti Canthini yang meninggalkanku untuk pria yang dicintainya. Aku menyesal tak pernah bisa mengerti perasaanmu yang terluka. Maafkan aku.”
Aku tak tahan untuk tidak menangis mengingat hari-hari sepi di Eropa selama aku berusaha melupakan seorang pria bernama Azhar Das yang tak seharusnya aku lupakan. Aku hanya bisa menunduk dan menangisi hal-hal yang telah kami ketahui. Azhar merangkul dan menenangkanku dalam pelukannya.
“Nanti malam kita akan datang ke pesta Nadya sebagai pasangan kekasih.”
Bisikan Azhar terdengar lembut di telingaku.
- Cinta yang Tersesat - 17 May 2015

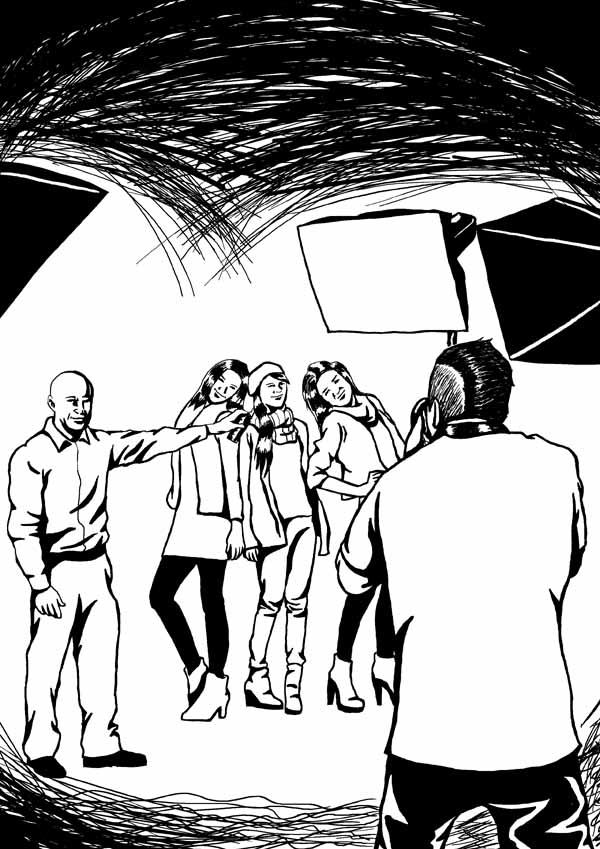
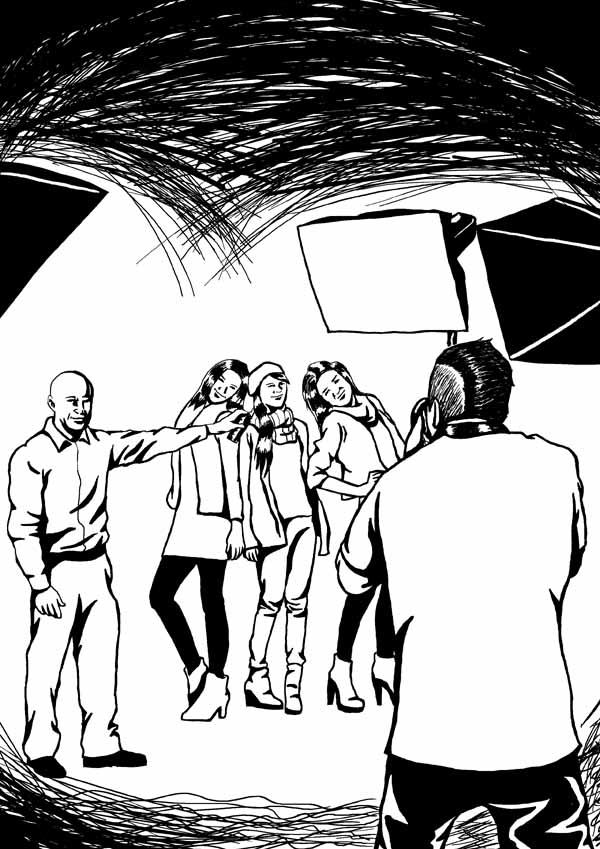
kadarwati TA
bagus… tapi kenapa ceritanya selalu seperti itu??? melarikan diri.
dhamalashobita
Suka ceritanya. Dibawakan dengan apik dan rapi. Makna yang disampaikan dalam cerita juga dalam dan disampaikan dengan baik. 🙂
Angel Rose
saia hampir menanggis membacanya, tapi karena sedang puasa jadi ditahan-tahan. Bagus bu ceritanya, suka 🙂
Fitri Wahyuningsih
Bagus, tapi rasanya membacanya belum sampai emosi yang maksimal. Ada perasaan haru, tapi masih terpendam. Sulit mengatakannya, tapi secara keseluruhan, sungguh nikmat dibaca. Karakter tokoh utamanya benar-benar terasa, gimana dia yang cuek dan sok nggak perhatian dengan perasaannya sendiri. Terimakasih sudah menulis cerita indah ini, Bu Yossy… ^^
Alivia Sasa
Hei Bu Yossy Wulandari Kusuma Ningrum. Jenengan juga berhak bahagia. Terima kasih sudah berbagi ^.^
Ping Madesta
Bagus dan cukup sulit ditebak akhir ceritanya.