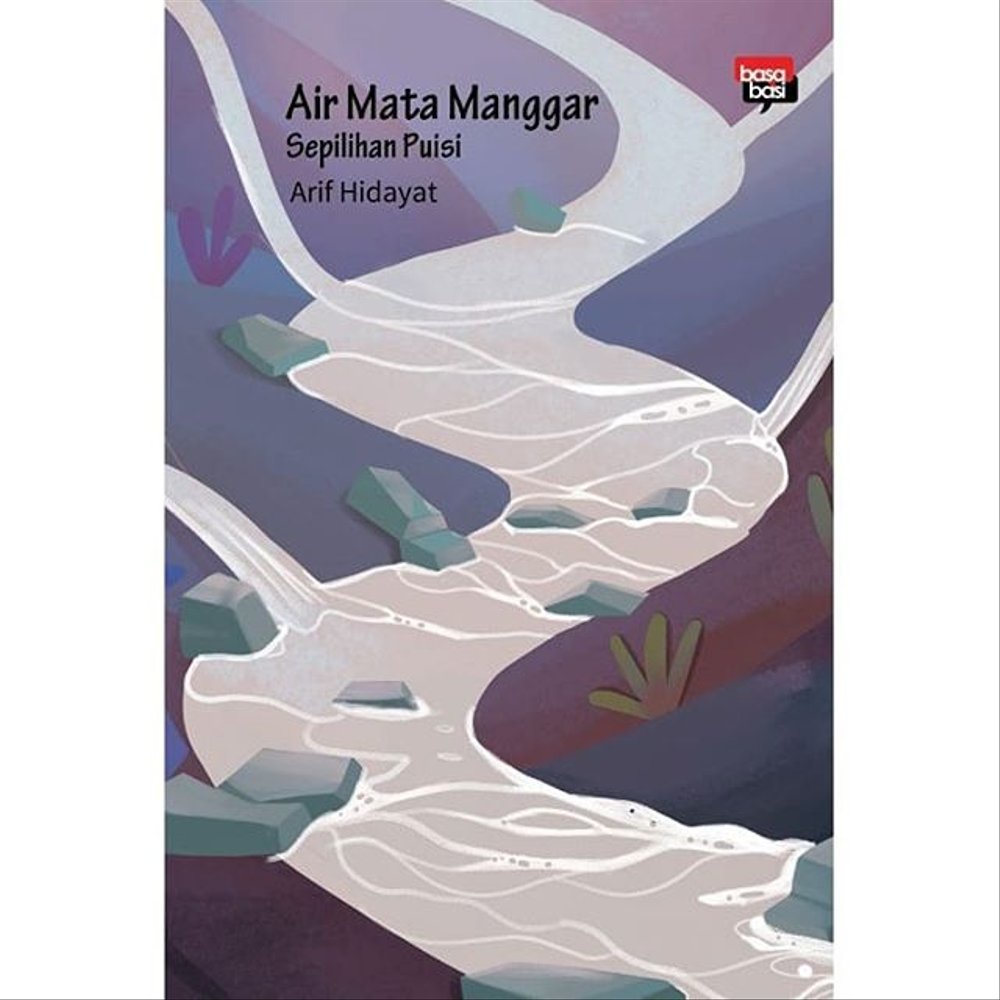
Judul : Air Mata Manggar
Penulis : Arif Hidayat
Tebal buku : 183 Hal.
Penerbit : Basabasi
Cetak : pertama, 2018
Betapa penting identitas bagi manusia. Agama dan filsafat sekurang-kurangnya ada pada posisi yang sama yang memungkinkan manusia mempertanyakan sekaligus menemukan identitasnya di dunia yang rawan ini.
Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa Arif Hidayat, melalui kumpulan puisi Air Mata Manggar (Basabasi, 2018), memilih jalan yang dianjurkan oleh Charles Baudelaire. Menurutnya, seorang seniman bertugas untuk menggambarkan pengalaman hidup yang cepat usai di tengah kota. “Kota” dipararelkan dengan “modernitas” yang mengalienasi manusia ke titik terrendah. Tema inilah yang banyak diangkat di dalam buku kumpulan puisi bernuansa liris nan murung.
Manusia modern akhir disebut-sebut sebagai manusia minimalis yang Deleuze dan Guattari sebut memiliki tiga tipifiksi: ironi, skizofrenia, dan fatalis.
…//Kota di negeriku telah berubah olehmu/pabrik-pabrik, pasar-pasar/dan langkah orang-orang tak tenang itu/merayakan kebisuan untuk memburu impian/yang berjalan di atas angin dan terjatuh di sore//Lihatlah, aku tak bisa membeli senyum yang segar/hanya ada kemasan air mata yang diawetkan/doa-doa kian langka dan mahal/Ketulusan hanya milik riwayat yang jauh/Kota sibuk meniru dan bising/untuk mendapatkan kebohongan yang sesaat//…
Kutipan puisi “Pulang ke Desa” di atas sesungguhnya menggambarkan kemurungan manusia urban yang kapitalistik dengan jargon industrilisme yang berpararel dengan simbol pabrik dan pasar. Nilai kemanusiaan menjadi luntur, tanpa empati: kemasan air mata yang diawetkan; demikian pun nilai religius yang tergerus: doa-doa kian langka dan mahal.
Sedikitnya, pembaca mendapat proyeksi manusia ironi yang merefleksi kecenderungan ke arah keyakinan tentang sifat ubah keyakinan dan kebenaran, meliputi ukuran-ukuran moral tentang baik-buruk, benar-salah. Mereka percaya adanya kriteria, tetapi kriteria tersebut selalu berubah dalam tiap keadaan yang berbeda. Karena kriteria yang tak menetap dan tanpa fondasi, sesungguhnya mereka tanpa kriteria.
//Aku menemukan diriku lagi lewat puisi/dengan kesepian-kesepian di bawah lampu/mengingat doa-doa yang pernah terpisah/seperti darat dan laut/Kota ini semakin panas/oleh isu isu pilitik./Betapa jalanan telah kehilangan malam/dan bencana kehilangan perhatian//Aku bisa hidup di dalam puisi/yang masih menyisakan air mata/pada cermin yang retak./Dan biarkan surat terbuka menjadi berita/yang lantas terlupa dan tak ada./Aku telah kehilangan suara/yang bergerak di jalan-jalan./Semua telah sunyi, kecuali pedagang keliling/dan rengek anak tetangga.//Di kamar ini, aku merenung/tentang kebebasan yang membunuh kebebasan/dan hidup yang dipenjara aturan./Aku merasa dijajah pengetahuanku sendiri/yang beralu bagai angin meninggalakan debu/bagai waktu yang tak bisa kembali.//Malam sepi. Aku hidup sendiri./Kau bernyanyi untuk sendiri/…
Penggalan puisi “Pada Sebuah Kamar” itu merupakan gambaran psikologis manusia skizofrenia yang mengalami matinya subjek. Dalam keadaan itu, manusia yang mengalami konsep diri terbelah atau bahkan jamak, tidak pernah memiliki ketetapan, konsisten, dan kontinuitas diri, sehingga menggiring pada ketiadaan ego dan subjek. Skizofrenia sebagai upaya pembebasan diri dari berbagai aturan keluarga, negara, bahkan agama, dalam rangka mengakui dan melepaskan segala dorongan purba manusia. Mereka yang membangkan terhadap kode-kode sosial, menciptakan manusia yang orphans, atheis, dan nomad.
//Setiap pagi, setiap aku minum kopi,/napasku dihubungkan oleh sinyal satelit/untuk bisa sampai pada impian cahayamu yang masih dingin./Aku berjalan dengan bayang-bayang melampaui batas/dan tak bisa membedakan diriku dengan kenyataan,/hingga aku berada dalam diriku dan tak bisa keluar.//Aku berjalan dengan anak-anak yang terjebak permainan,/anak-anak yang tak menemukan jiwanya dari orangtua mereka./Anak-nak itu lahir dari pemberitahuan yang menyenangkan/seperti kabar surga dari Tuhan./Aku membaca surat kabar yang secepat angin/dan merasa memilikiki dunia anpa membagi dengan sesiapa/ pun/…
Bagian puisi “Internet” di atas adalah lukisan manusia fatalis yang terserap ke dalam logika objek (internet, gadget, tv, fashion, komoditi, gaya hidup, dll.) yang tidak dapat menjelaskan dirinya. Manusia fatalis dibentuk oleh kondisi fatalitas, yaitu saat segala sesuatu (konsep, argumen, sistem atau objek) berkembang ke arah titik ekstrem, kondisi itu terus didorong sampai pada titik setiap konsep, komunikasi, informasi, sistem, atau objek kehilangan logikanya.
Alih-alih memperlihatkan kemajuan peradaban yang justru mendistorsi kemanusiaan, Arif Hidayat menawarkan jalan pembebasan atas kuasa modernitas itu sendiri melalui puisi-puisinya. Tawaran itu adalah jalan asketis untuk membaca sejarah. Sebab, manusia modern adalah ahistoris, yang terputus dari sejarahnya.
Meskipun Arif Hidayat selalu tergoda untuk beratraksi dengan alegori yang meliuk-liuk sekan ingin menjangkau semua ceruk atau detail dalam puisi-pusinya sehingga kadang terasa sangat menguras energi, pembaca akan selalu dipandu untuk menemukan sebuah titik simpul sebagai suatu elaborasi wacana. Tentu, strategi estetika ini tak akan terlalu menarik bagi pembaca yang cenderung menyukai puisi-puisi semisal Ahmad Yulden Erwin atau SDD.
Betapa pun, buku kumpulan puisi Air Mata Manggar ini telah menjadi pengobat dahaga akan munculnya nama penyair kelahiran Banyumas Raya dalam blantika sastra Indonesia mutakhir setelah maestro fiksi kenamaan yang lekat pada diri Ahmad Tohari. Semoga.
- Manusia Ironi dalam Air Mata Manggar - 27 July 2019
- Personalitas dan Spiritualitas Ahmad Tohari - 20 February 2019
- Baturraden dan Mitos Putus Cinta yang Mulai Terlupakan - 22 February 2017


Pro-Fanny
Sejak kapan ada “kota” tanpa pabrik dan pasar?
Yulianda
keren